Dari Aksi Kolektif ke Gaya Hidup
Setiap kali ada kampanye lingkungan, kita diajak ikut: tanam pohon, kurangi plastik, hemat air, daur ulang. Semua terdengar heroik. Tapi kalau ditanya jujur, seberapa besar pengaruhnya terhadap krisis iklim yang makin nyata?
Ilusi partisipasi adalah tentang itu — tentang bagaimana kita dibuat merasa terlibat, padahal sistemnya tetap jalan seperti biasa.
Narasi “semua orang bisa berkontribusi” terdengar manis. Ia memberi rasa punya andil, membuat kita merasa berguna. Tapi di baliknya, ada pergeseran besar: dari tanggung jawab kolektif menjadi tanggung jawab individu.
Kita disuruh menghitung jejak karbon pribadi, tapi jarang diminta menantang siapa yang sebenarnya menguasai emisi global. Menurut laporan CDP (2017), hanya 100 perusahaan besar yang menyumbang lebih dari 71% total emisi karbon di dunia.
Namun setiap hari yang diingatkan tetap sama: “Jangan lupa bawa tumbler.”
Nggak salah membawa tumbler, tentu. Tapi kalau itu jadi fokus utama, maka kita sedang menatap bayangan sendiri, bukan akar masalahnya.
Inilah wajah greenwashing paling halus: membuat kita sibuk memperbaiki diri, agar lupa memperbaiki sistem.
Dari Tanggung Jawab ke Rasa Bersalah
Industri besar dan pemerintah suka memakai narasi partisipasi karena aman — tidak menyinggung kekuasaan. Kalimat seperti “kita semua bagian dari solusi” terdengar egaliter, tapi sebenarnya menutupi ketimpangan.
Faktanya, tidak semua orang punya kontribusi yang sama terhadap lingkungan. Dan tidak semua orang merasakan dampak yang sama dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Kita diminta merasa bersalah karena belum cukup hijau.
Kita disuruh menanam pohon, sementara hutan di Kalimantan terus dibabat untuk proyek nikel dan sawit.
Ironinya, banyak program reboisasi itu dibiayai oleh perusahaan energi fosil yang mendapat subsidi triliunan rupiah per tahun (IEA, 2023).
Inilah yang disebut green guilt — rasa bersalah hijau yang membuat kita sibuk menebus dosa kecil, sementara dosa besar dibiarkan utuh.
Kita jadi percaya bahwa mencuci pakaian sintetis lebih bersih daripada mencuci sistem ekonomi yang kotor.
Dalam studi sosial, ini disebut participation without power — partisipasi tanpa kekuasaan.
Kita boleh ikut kampanye, ikut webinar, ikut menanam, tapi tidak pernah dilibatkan dalam keputusan kebijakan iklim yang menentukan masa depan bumi.
Kita hanya figuran di foto proyek sustainable development, bukan suara di ruang rapat tempat arah dunia ditentukan.
Partisipasi yang Terlihat, Kekuasaan yang Tak Tersentuh
Coba lihat proyek REDD+ di Papua yang diklaim menyelamatkan hutan. Di atas kertas tampak hijau, tapi masyarakat adat jarang benar-benar dilibatkan.
Lalu ada food estate di Kalimantan Tengah yang dijual sebagai solusi pangan nasional.
Faktanya, proyek itu merusak gambut, menggusur petani kecil, dan memperparah ketimpangan lingkungan.
Semua diberi label “partisipatif,” padahal kenyataannya tetap top-down dan eksploitatif.
Inilah ilusi partisipasi yang paling berbahaya: ketika aksi terlihat ramai, tapi kekuasaan tetap tak tersentuh.
Krisis iklim tidak akan selesai dengan lomba daur ulang plastik atau ajang penanaman sejuta pohon tanpa reformasi kebijakan.
Kita butuh partisipasi publik yang sejati — yang bisa mengguncang arah kebijakan, bukan sekadar mengisi kolom petisi online.
Yang mampu menantang greenwashing korporasi, bukan sekadar meniru kampanye media sosial mereka.
Karena krisis ini bukan soal siapa yang ikut aksi, tapi siapa yang memegang kendali atas bumi.
Dari Ilusi ke Kesadaran
Di Indonesia, beberapa contoh mulai muncul.
Komunitas WALHI, Jeda Untuk Iklim, dan Extinction Rebellion Indonesia membangun ruang perlawanan ekologis dari bawah.
Mereka tidak hanya menanam pohon, tapi menanam kesadaran politik — bahwa keadilan iklim lahir dari keberanian menggugat kekuasaan.
Di pesisir Demak dan Kendari, kelompok nelayan ikut menolak proyek reklamasi dan tambang pasir laut. Bagi mereka, menjaga laut bukan aktivisme — tapi bertahan hidup.
Di situ letak makna aksi iklim yang sejati: bukan kampanye viral, tapi gerak sadar dari bawah yang menolak jadi korban.
Kita bisa mulai dari hal sederhana: menolak ilusi. Menolak percaya bahwa perubahan cukup dimulai dari konsumsi pribadi.
Karena yang perlu diubah bukan cuma gaya hidup, tapi sistem yang membuat gaya hidup itu jadi satu-satunya pilihan.
Ilusi partisipasi dalam krisis iklim bukan sekadar tentang kampanye.
Ia tentang siapa yang berhak menentukan arah perubahan — dan siapa yang diam-diam menulis ulang masa depan kita.
Dan seperti yang sering gw rasain, kita ini bukan kekurangan aksi. Kita cuma kehilangan keberanian buat menantang sumber masalahnya.






















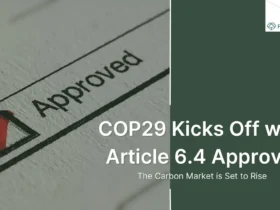



Leave a Reply