Ekologi Politik muncul terkait sumberdaya alam selama ini disikapi sebagai masalah teknis, implikasinya, kebijakan yang diterapkan-pun bersifat teknis. Sebagai contoh, Ketika terjadi banjir di wilayah Jakarta, maka yang dicari solusi adalah bagaimana pompanisasi air dan normalisasi saluran kanal yang menghubungkan ujung Jakarta. Pun Ketika ada masalah pencemaran suangai di wilayah pertambangan di Kalimantan timur, solusi yang diambil adalah mencari teknologi yang ramah lingkungan yang tidak mengganggu ekosistem air. Pertanyaanya sekarang, apakah solusi tersebut keliru?
Tentu saja tidak. Semua pengambil kebijakan memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi masalah yang ada. Namun, selama masalah sumberdaya dipahami sebagai masalah yang sifatnya teknis, maka solusi yang diambil oleh para pengambil kebijakan-pun akan teknis. Pertanyaan selanjutnya, apakah solusi teknis yang diambil dapat menyelesaikan masalah atau justru akan menimbulkan masalah baru?. Apakah Ketika banjir melanda dan diatasi dengan normalisasi lalu masalah bisa selesai?, siapa yang terdampak dari masalah dan kebijakan yang diambil? Bukankah rakyat, negara, pengusaha, pedagang juga ikut terdampak dari masalah tersebut?.
Beberapa contoh kasus diatas menggambarkan bahwa ternyata persoalan sumberdaya tidak semata masalah teknis, ia juga bisa menjadi masalah sosial, bahkan politik karena berkaitan dengan pemanfaatan atau kontrol atas sumberdaya. Oleh karenanya, saking pentingnya pembahasan masalah sumberdaya alam dan sosial-politik, maka para akademisi membahas lebih dalam dengan pendekatan ekologi politik atau political ecology.
Politik–Ekologi
Politik Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungannya,tujuannya bukan hanya menjelaskan fenomena perubahan lingkungan, namun juga mereformulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan.
Konsep politik ekologi mulai berkembang sejak 1970an dan awal 1980an, namun istilah ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1967 oleh Russet. Ekologi menurut Russet menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kehadirannya lebih diwarnai sebagai antitesa dari konsepsi pembangunan yang lahir terutama pada revolusi industri dan pembangunan kembali bangsa-bangsa karena perang dunia ke II. Fokus sebenarnya pada perebutan kekuasaan dalam tata Kelola lingkungan dengan melibatkan para aktor, institusi, kelompok dan identitas tertentu dari asset materi (sumberdaya alam).
Ekologi politik awalnya merupakan pengembangan dari kajian ekologi budaya. Escobar (2006) berpendapat bahwa kerangka political ecology dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan dan kesamaan akses dalam konflik distribusi ekonomi, ekologi, dan budaya.
Turner (2004) juga berpendapat bahwa konflik sumber daya telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berbeda dari kelompok sosial yang berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya.
Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Imam Mujahidin mengungkapkan bahwa perspektif ekologi politik dikonseptualisasikan dengan penekanan pada tiga kerangka teoritis.
Pertama, dialektika lingkungan sosial.
Kedua, konstruktivisme lingkungan, dan
Ketiga, produksi bersama socionature.
Ketiga kerangka tersebut berasal dari kritik tentang bagaimana hubungan alam-masyarakat diteorikan dalam penjelasan berbagai masalah manusia-lingkungan dan solusinya.
Kerangka kerja ini juga terinspirasi dari konsep reduksionisme neo-Malthus tentang degradasi lahan atau kritik terhadap gagasan degradasi lahan itu sendiri. Perspektif teoretis dan metode penelitian terkait ini menggambarkan keterlibatan ekologi politik dengan tetap mengacu pada aspek ontologis dan epistemologis fundamental yang menjadi ciri perdebatan alam-masyarakat.
5 Pendekatan Ekologi Politik
Pendekatan yang diambil dalam ekologi politik berbeda satu sama lain namun saling melengkapi. Bryant dan Bailey (2001) memetakan pendekatan ekologi politik menjadi 5:
Pertama, Pendekatan yang bertumpu pada masalah Iingkungan secara spesifik. Pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian traditional geography yang berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik.
Kedua, Pendekatan yang bertumpu pada konsep yang terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yakni mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi. Analisis wacana nampaknya dominan dalam pendekatan ini. Seperti analisis terhadap wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat dan alam serta ekonomi-politik yang membuat asumsi itu ada.
Ketiga, Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertent seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika, dan seterusnya.
Keempat, Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas gender dan etnik.
Kelima, Pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan. karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.
Politik Ekologi
Politik ekologi adalah cara pandang dalam memahami persoalan hubungan antara manusia dan lingkungan. Cara pandang ini banyak dipengaruhi dari pemikiran neo-marxian tentang underdevelopment, sebagai kritik dari pendekatan Malthusian dan cultural ecology selama ini.
Oleh karenanya, cara pandang politik ekologi ini lebih menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan semata disebabkan oleh persoalan internal dalam lingkungan tersebut. Tetapi karena pengaruh tekanan politik dan ekonomi. Oleh karenanya, konsekuensi pola hubungan manusia dengan alam lebih dipengaruhi oleh adanya pelabelan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Ini lah yang kemudian dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran.
Pandangan ini relatif berbeda dengan pandangan kaum ekologi yang memandang relasi manusia dengan alam disebabkan karena tekanan internal. Seperti jumlah penduduk (Malthusian) dan persoalan ekplorasi dan konservasi.
Pandangan ekologi aliran Malthusian menyatakan bahwa jika populasi penduduk bertambah, maka kebutuhan terhadap makanan akan bertambah. Dengan keterbatasan sumberdaya alam, maka akan terjadi persaingan makanan, akibatnya berpotensi terjadi kelaparan dan ekspolitasi berlebihan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, aliran Malthusian berkesimpulan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka jumlah penduduk harus dikendalikan dengan berbagai kebijakan.
Berbeda dengan Malthusian, menurut aliran politik ekologi, pola hubungan manusia dengan lingkungan bukanlah persoalan kepadatan penduduk. Namun lebih disebabkan ketidakmerataan (inequality) dan faktor tekanan kekuasaan. Oleh karenanya, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya bawah persoalan kerusakan lingkungan lebih disebabkan karena faktor eksternal yang sifatnya global.
Baca juga Tips Dunia Pertanian dan Klinik Autism di Depok
















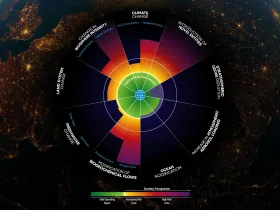










Leave a Reply